Benarkah Banyak Pengangguran di Sumbar?

Sumbar,kpktipikor.id – Sabtu 04 Oktober 2025 TAK ada orang yang ingin jadi pengangguran. Konsekuensinya berat. Susah. Dan, hidup butuh uang. Mendapatkan uang, harus bekerja.
Di Sumatra Barat (Sumbar), persoalan pengangguran selalu menjadi perbincangan hangat. Data terbaru BPS per Februari 2025 menempatkan provinsi ini dalam 10 besar pengangguran tertinggi di Indonesia. Potret itu sebagai tanda krisis ekonomi dan lemahnya daya serap tenaga kerja di Sumatra Barat.
Namun, apakah benar realitas di lapangan sesuram angka yang tercatat? Ataukah kita sedang terjebak pada definisi lama tentang kerja, yang masih sempit memandang pekerjaan hanya sebatas kantor, gaji bulanan, dan instansi formal?
Dalam masyarakat Minangkabau, kerja sejatinya bukan semata-mata tentang menjadi pegawai. Sejak dahulu, orang Minang terbiasa hidup dari perdagangan, berdagang ke rantau, atau mencari penghidupan dengan cara yang fleksibel dan kreatif. Maka, ketika statistik menunjukkan Sumatra Barat memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka 5,69%, mungkin pertanyaan yang lebih relevan adalah: apakah para pemuda Minang sungguh menganggur, atau justru sedang bekerja dalam ruang-ruang baru—digital, informal, dan lintas batas geografis—yang tidak tercatat dalam tabel resmi negara?
Secara metodologis, BPS menghitung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap pada periode survei. Artinya, mereka yang bekerja di luar sistem formal, tidak bergaji tetap, atau mengandalkan pekerjaan lepas bisa saja masuk kategori “penganggur.”
Di Sumatra Barat, banyak anak muda bekerja sebagai freelancer, digital creator, driver ojek online, pedagang daring, bahkan pekerja jarak jauh (remote worker) untuk perusahaan luar negeri. Aktivitas ini menghasilkan uang, memberi ruang kreativitas, serta membuka peluang jejaring global, meski tidak tercatat sebagai pekerjaan resmi dalam survei ketenagakerjaan.
Di sinilah letak paradoksnya: secara statistik, angka pengangguran tinggi, namun secara faktual, banyak anak muda Minang justru sedang bertransformasi ke dalam pola kerja baru yang lebih fleksibel dan digital.
Pertanyaan yang lebih penting: apakah anak muda Sumbar benar-benar menganggur, ataukah mereka sekadar tidak terdata dalam kerangka pekerjaan formal? Sebuah pekerjaan di dunia digital tidak selalu meninggalkan jejak administrasi yang bisa dihitung negara. Bahkan seorang pemuda Minang di Padang bisa saja mendapatkan penghasilan dolar dari menjual jasa desain grafis kepada klien di Eropa, atau seorang anak nagari di Bukittinggi menjadi penulis konten untuk perusahaan di Jakarta.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pengangguran di Sumbar tidak bisa hanya dilihat dalam kacamata klasik. Ada yang memang tidak bekerja sama sekali, ada yang tidak mendapatkan pekerjaan formal, dan ada pula yang bekerja dengan cara-cara baru yang tidak terdaftar dalam data survey.
Dalam tradisi Minangkabau, merantau adalah jalan hidup. Laki-laki Minang sejak lama didorong untuk meninggalkan kampung halaman, bukan karena tidak mencintai nagari, melainkan justru sebagai bentuk tanggung jawab dan cinta.
Sistem matrilineal membuat harta pusaka diwariskan kepada perempuan, sementara laki-laki dituntut untuk mencari jalan hidup sendiri.
Merantau bukan hanya untuk mengisi perut, melainkan juga untuk mengasah kemandirian, menguji kedewasaan, dan memperluas wawasan.
Pepatah mengatakan: “Karatau madang di hulu, babuah babungo balun. Marantau bujang dahulu, di kampuang baguno balun.” Seorang bujang yang belum pernah merantau dianggap belum masak, belum menemukan dirinya sepenuhnya.
Kini, filosofi merantau menghadapi era baru. Merantau tidak lagi selalu berarti fisik berpindah ke tanah Jawa, Malaysia, atau Singapura. Merantau bisa berarti menjelajahi ruang digital, bekerja lintas batas geografis, dan mengirimkan “uang” serta gagasan pulang ke kampung halaman tanpa harus berangkat dengan kapal laut atau pesawat terbang.
Anak muda Minang hari ini sesungguhnya masih menjalankan filosofi merantau, hanya saja bentuknya berubah. Mereka merantau secara digital—masuk ke dunia global melalui gawai, menembus pasar dunia tanpa harus meninggalkan rumah gadang.
Pekerjaan seperti content creator, programmer, desainer, penulis lepas, atau marketing digital adalah wujud baru dari “rantau” itu sendiri.
Kalau dulu seorang perantau membawa pulang emas atau hasil berdagang, sekarang ia bisa membawa pulang ide, jaringan, bahkan investasi digital untuk membangun nagari.
Namun, problem yang muncul adalah kesenjangan antara cara pandang lama dengan pola hidup baru. Orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah masih sering menilai pekerjaan itu “tidak nyata” atau “tidak jelas.” Padahal, jika ditelusuri, penghasilan mereka kadang lebih besar daripada pegawai kantoran dengan gaji tetap.
Idealnya, merantau di era kini bukan sekadar meninggalkan kampung atau masuk dunia digital, melainkan bagaimana menggabungkan nilai lama dengan tantangan baru.
Nilai tanggung jawab pada keluarga dan kampung halaman tetap penting, karena filosofi Minang menekankan “pulang membawa hasil.”
Tetapi hasil itu kini tidak harus berupa uang tunai semata—bisa berupa ilmu, teknologi, atau bahkan jaringan kerja sama internasional yang bermanfaat untuk nagari.
Di sisi lain, pemerintah daerah Sumatra Barat juga harus memperluas perspektif dalam membaca realitas kerja. Angka pengangguran yang tinggi harus dijawab bukan hanya dengan mencetak pegawai baru, melainkan dengan menciptakan ekosistem digital yang sehat: akses internet merata, pelatihan teknologi, dan dukungan terhadap industri kreatif. Dengan begitu, filosofi merantau bisa terus relevan, dan anak-anak muda Sumbar bisa tetap “mambangkik batang tarandam” dengan cara mereka sendiri.
Sumatra Barat memang tercatat sebagai provinsi dengan pengangguran tinggi. Tetapi, jika kita membaca realitas lebih jauh, banyak pemuda Minang sejatinya tidak benar-benar menganggur. Mereka hanya bekerja di jalur yang berbeda, jalur yang belum sepenuhnya dipahami dalam kategori statistik resmi.
Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang. Filosofi merantau mengajarkan bahwa hidup adalah tentang berani keluar dari zona nyaman, menjemput pengalaman, dan kembali dengan sesuatu yang berguna.
Merantau digital adalah kelanjutan dari semangat itu. Yang perlu dijaga adalah akarnya—nilai tanggung jawab, cinta kampung halaman, dan keberanian—serta sayapnya: kemampuan menjelajahi dunia baru, termasuk dunia maya.
Dengan begitu, pengangguran bukan sekadar angka, melainkan pintu untuk memahami bahwa kerja hari ini punya banyak wajah, dan merantau tidak pernah berhenti, hanya berubah bentuk. (Mardius)
Aturan Tentang Dana Desa di Indonesia Guna untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
kpktipikor.id-Sabtu 04 Okiber 2025
Aturan tentang Dana Desa di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah penjelasan ringkas mengenai aturan penggunaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat, beserta dasar hukumnya:
—
📜 Dasar Hukum Dana Desa
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (dan perubahanny).
3. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi (Permendes PDTT):
Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (yang berlaku untuk tahun anggaran 2025 juga bisa mengacu pada ini jika belum ada revisi baru)
—
🎯 Tujuan Dana Desa
1. Meningkatkan pelayanan publik di desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa.
5. Memajukan ketahanan sosial dan budaya desa.
—
✅ Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat
Berdasarkan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2023, prioritas penggunaan Dana Desa difokuskan pada:
1. Pemulihan Ekonomi
Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Dukungan terhadap UMKM lokal.
Pengembangan desa wisata, pertanian, perikanan, dan peternakan.
Program padat karya tunai desa (PKTD) — memberdayakan masyarakat miskin dan menganggur melalui proyek-proyek desa.
2. Program Prioritas Nasional
Penurunan stunting.
Peningkatan akses air bersih dan sanitasi.
Pendidikan dasar dan kesehatan masyarakat desa.
Perbaikan gizi dan posyandu.
3.Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan teknologi tepat guna.
Penguatan kapasitas kelompok tani, nelayan, perempuan, dan pemuda.
Bantuan langsung tunai (BLT Dana Desa) untuk warga miskin ekstrem.
4. Pembangunan Infrastruktur Desa
Jalan desa, jembatan, irigasi, embung, saluran air.
Rumah layak huni untuk warga miskin (terbatas).
Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
—
💰 BLT Dana Desa
Program ini wajib dianggarkan setiap tahun untuk warga miskin ekstrem, dengan syarat:
Maksimum 25% dari total Dana Desa.
Diberikan kepada keluarga miskin yang belum menerima bantuan lain (PKH, BPNT, dll).
Nilai BLT: biasanya Rp300.000/bulan per keluarga (dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah).
—
📌 Catatan Penting
Penggunaan Dana Desa harus berdasarkan Musyawarah Desa.
Dikelola secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat desa.
Harus tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).(Mardius)



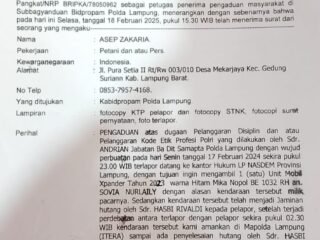



















Tidak ada komentar