Menteri Koboi di Republik Bandit: Fenomena Purbaya Kejujuran di Tengah Negara yang Tersesat Arah

Opini, kpktipikor.id-19 Oktober 2025- INDONESIA nampaknya semakin kehilangan arah dalam mengelola rumah besarnya sendiri. Di tengah gegap gempita pembangunan dan jargon pertumbuhan ekonomi, kita justru menyaksikan negara-negara yang seolah-olah “salah urus”. Benang kusut kebijakan publik yang tidak sinkron, tumpang tindih regulasi, dan tata kelola keuangan negara yang amburadul, mencerminkan betapa lemahnya arah kepemimpinan yang berlandaskan akuntabilitas dan moral publik.
Dari sektor hukum hingga birokrasi fiskal, gejalanya seragam yakni negara tampak dikuasai oleh kartel kepentingan, bukan lagi oleh nurani dan kebangsaan. Keadilan menjadi barang mewah, hanya dapat diakses oleh mereka yang punya koneksi dan modal. Lembaga-lembaga penegak hukum kerap beroperasi layaknya pedagang jasa hukum, bukan pengawal keadilan. Sementara rakyat, yang setia membayar pajak dan menanggung beban hidup yang terus meningkat, hanya menjadi penonton dalam drama kemerosotan lembaga moral negara.
Dalam situasi itulah muncul sosok Purbaya, Menteri Keuangan yang dikenal ceplas-ceplos, lugas, dan berani menyentuh akar persoalan keuangan negara. Gaya bicaranya yang terbuka, kadang dianggap tidak diplomatis, tapi sebenarnya adalah cermin kegelisahan masyarakat yang lama terpendam. Ia bukan sekadar bicara soal angka dan defisit, melainkan tentang integritas dan pengelolaan uang rakyat yang jauh dari asas transparansi.
Berbicara Apa Adanya di Tengah Budaya Pura-pura
Sosiolog Robert Bellah dalam Habits of the Heart menulis bahwa masyarakat yang kehilangan orientasi moral masyarakat cenderung memusuhi kejujuran yang mengganggu kenyamanan status quo. Fenomena itulah yang kini dialami Indonesia. Ketika Purbaya membuka tabir bobroknya pengelolaan keuangan negara, sebagian elite justru menudingnya “tidak etis”, “pencitraan”, atau “terlalu ikut campur”.
Padahal, dalam sistem yang sehat, kritik internal pejabat publik seharusnya menjadi mekanisme koreksi diri negara. Namun di Indonesia, kejujuran pejabat sering dianggap menghina koleganya sendiri.
Data dari Transparency International (2024) menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan di angka 34, tidak bergerak signifikan dalam lima tahun terakhir. Sementara laporan BPK semester I tahun 2025 mencatat potensi kerugian negara mencapai Rp72 triliun akibat kerugian pengelolaan keuangan di berbagai instansi pusat dan daerah. Angka-angka itu bukan sekadar statistik, ia menggambarkan betapa parahnya penyakit struktural yang coba dibedah Purbaya.
Fenomena Purbaya sesungguhnya menampilkan betapa bangsa ini sedang terjangkit rabun kebenaran, tidak mampu lagi membedakan mana yang tulus, mana yang pura-pura. Setiap narasi kejujuran dianggap “tidak santun”, setiap upaya dianggap “mengganggu harmoni”, dan setiap pejabat yang berani berpikir benar diposisikan sebagai “musuh bersama”.
Dalam konteks sosiologi politik, fenomena serupa dengan yang disebut Hannah Arendt sebagai “banality of evil”, situasi ketika kejahatan menjadi biasa karena dilakukan secara sistematis oleh sistem yang kehilangan hati nurani.
Masyarakat pun akhirnya terbiasa hidup dalam paradoks: menyalahkan sistem, tapi takut pada perubahan. Kita mengeluh soal korupsi, tapi memusuhi pejabat yang berani melawannya. Kita menuntut transparansi, tapi mencemooh keberanian yang menyingkapkan tabir busuk di baliknya.
Purbaya mungkin bukan sosok sempurna. Ia bisa salah dalam diksi, bisa salah dalam retorika. Tapi keberaniannya berbicara jujur di tengah budaya kepura-puraan birokrasi adalah oase langka. Ia mengingatkan kita pada pesan klasik Albert Camus bahwa “Kebebasan sejati adalah berbicara kebenaran, meski dunia membencimu karenanya.”
Pertanyaannya kini, apakah bangsa ini masih memiliki ruang bagi kejujuran seperti itu? Atau kita sudah terlalu nyaman hidup dalam ilusi, hingga lupa menjadi manusia yang menolak.
Penulis: Sri Radjasa, M.BA.
( Pemerhati Intelejen ).
Artikel ini merupakan opini penulis, seluruh isi diluar tanggung jawab redaksi, sepenuhnya tanggung jawab penulis.










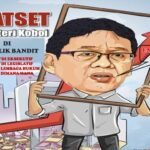












Tidak ada komentar